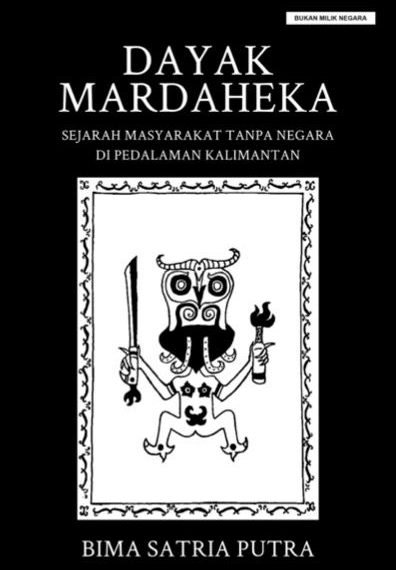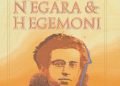Buku ini hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi narasi kolonial dalam penulisan sejarah Indonesia, khususnya sejarah masyarakat Dayak. Alih-alih menjadi objek pasif dalam sejarah, orang Dayak dihadirkan sebagai subjek aktif yang berpikir, memilih, dan melawan. Penulis menggunakan pendekatan dekolonial untuk membongkar warisan kekuasaan yang masih mengakar dalam cara kita memahami masyarakat adat hingga hari ini.
Bab I “Dayak Mardaheka”
Bab ini membuka dengan kritik terhadap citra Dayak yang sering dianggap terbelakang, terisolasi, dan tidak berperadaban. Padahal, masyarakat Dayak memiliki struktur sosial dan pengetahuan sendiri yang tidak kalah maju.
Penulis menekankan bahwa “merdeka” bagi Dayak bukan hanya bebas dari penjajahan politik, tapi juga bebas dari pengetahuan yang menjajah, yaitu narasi-narasi yang dibentuk oleh penjajah dan diwarisi oleh sejarah resmi.
Bab II – “Penjajahan atas Dunia Dayak”
Di sini penulis membahas bagaimana penjajahan dilakukan melalui pengetahuan dan penguasaan ruang hidup:
1. Pemetaan dan Penamaan Kolonial
Peta dibuat oleh kolonial Belanda (dan Inggris) untuk menaklukkan wilayah yang belum mereka kuasai secara penuh. Dalam proses ini, peta bukan hanya sekadar alat navigasi atau dokumentasi geografis, tapi alat kuasa.
Dalam peta kolonial, banyak nama-nama lokal yang dihapus atau diubah, digantikan dengan istilah-istilah baru yang sesuai dengan lidah dan logika penjajah. Misalnya, sungai, gunung, hutan, dan permukiman diberi nama kolonial, menghilangkan jejak toponimi lokal.
Hal ini menandai bahwa penjajah tidak hanya mengklaim tanah secara fisik, tapi juga menghapus identitas budaya yang melekat pada ruang.
Yang di mana maknanya ialah; Pemetaan kolonial adalah bentuk awal dari penguasaan, menggambar peta berarti menentukan batas kekuasaan. Mengubah nama berarti menguasai makna.
2. Ilmu sebagai Alat Kuasa
Ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menulis tentang masyarakat Dayak mayoritas berasal dari pandangan luar, yaitu para penjelajah, misionaris, pejabat kolonial, dan etnolog Barat.
Mereka datang membawa cara pandang Eropa (eurocentrism) dan menilai Dayak berdasarkan standar budaya Barat.
Hasil tulisan mereka menggambarkan Dayak sebagai:
“liar”
“belum beradab”
“tak punya sistem sosial”
Narasi ini kemudian disebarluaskan dan menjadi dasar kebijakan kolonial, baik dalam misi penginjilan, pendidikan, maupun penguasaan lahan.
Efeknya:
Pengetahuan ini menjadi semacam “legitimasi intelektual” bagi penjajahan. Karena jika Dayak dianggap tidak memiliki sistem, maka dianggap sah untuk “mendidik”, “menata”, atau bahkan “menguasai” mereka.
”Ilmu yang tidak lahir dari suara lokal justru bisa menjadi alat penaklukan. Maka, dekolonisasi pengetahuan menjadi penting agar suara masyarakat Dayak bisa kembali hadir dalam sejarah mereka sendiri.”
3. Pajak, Bajak & Budak
a. Pajak:
Pajak adalah instrumen kolonial untuk memaksa masyarakat Dayak masuk ke dalam ekonomi uang (moneter), yang sebelumnya tidak mereka gunakan.
Sistem ekonomi Dayak bersifat subsisten dan berbasis komunal. Dengan mewajibkan pajak, mereka dipaksa menanam komoditas tertentu (misalnya karet, kopi) untuk dijual, agar bisa membayar pajak.
Mereka yang tidak mampu membayar akan dikenai sanksi hukum atau kerja paksa.
b. Bajak:
Bajak di sini bukan sekadar membajak sawah, tapi merujuk pada eksploitasi hasil bumi dan sumber daya lokal.
Tanah-tanah adat dirampas atau dikuasai dengan alasan “tidak produktif” menurut logika kolonial.
Hutan dibuka, sungai dikuasai, dan hasil alam Dayak dijadikan komoditas ekspor.
c. Budak:
Mereka yang tidak membayar pajak, menolak aturan kolonial, atau dituduh “melawan”, dijadikan tenaga kerja paksa.
Praktik ini sering dibungkus dalam istilah “kerja rodi” atau “kerja wajib”.
Dalam beberapa kasus, juga terjadi perbudakan internal, di mana masyarakat Dayak dijual atau diperdagangkan oleh perantara lokal yang bersekutu dengan penjajah.
Makna dari Ketiganya menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya soal kekuasaan negara, tapi juga soal penghisapan ekonomi dan penghancuran struktur sosial-budaya.
Bima menyimpulkan bahwa masyarakat Dayak bukan “primitif” yang belum kenal negara, melainkan mereka secara sadar memilih menolak bentuk-bentuk kekuasaan yang eksploitatif. Mereka tidak tunduk pada pajak sepihak, tidak percaya pada negara yang hanya datang untuk mengambil, dan melawan lewat migrasi, perlawanan senjata, atau menyembunyikan komunitasnya.
Di sub bab ini saya menyimpulkan bahwa negara bisa hadir tanpa kebaikan publik, hanya sebagai struktur pengambilan dan kekerasan.
Ini juga membalik narasi bahwa negara = kemajuan; justru dalam konteks Dayak, negara hadir sebagai pelaku kekerasan struktural dan ekonomi.
Penulis: Rahma
Editor: M Yusrifar